Kolom
Peluang Agribisnis di Sektor Perikanan: Tantangan dan Strategi
Published
8 bulan agoon
By
Cimahi Pos

oleh Amtool Nur
Mahasiswi Jurusan Agribisnis, Fakuktas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Jakarta
Pembangunan sektor perikanan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan potensi lestari perikanan tangkap laut sekitar 12,01 juta ton per tahun menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadikan sektor perikanan sebagai lokomotif ekonomi nasional.
Sektor ini tidak hanya menyediakan protein hewani yang vital bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi sekitar 16,42 juta orang yang bergantung langsung pada kegiatan perikanan dan kelautan.
Subsektor perikanan menempati posisi strategis dalam agribisnis karena memiliki pertumbuhan positif meskipun di tengah tekanan global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 6,25 miliar, naik dari tahun sebelumnya, dengan komoditas utama yaitu Udang, Tuna, Kerapu, Kakap, Tenggiri, Tilapia, Cephalopoda (squid, octopus, cuttlefish), Daging kepiting ranjungan, Kepiting, Rumput laut, Teripang, Lobster.
Permintaan akan produk perikanan terus meningkat seiring bertambahnya populasi dunia, kesadaran terhadap makanan sehat, serta preferensi masyarakat urban terhadap sumber protein rendah lemak dan bernutrisi tinggi. Fenomena ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasarnya, baik dalam ekspor langsung maupun melalui diversifikasi produk olahan seperti fillet ikan, surimi, atau pakan hewan berbasis laut.
Namun, potensi tersebut masih belum tergarap optimal karena berbagai tantangan yang kompleks. Sebagian besar nelayan Indonesia tergolong nelayan kecil dengan alat tangkap tradisional, keterbatasan modal, serta rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar. Masih banyak daerah pesisir yang belum memiliki fasilitas pendingin atau cold storage, sehingga ikan hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar. Misalnya, di Maluku dan Papua yang merupakan lumbung perikanan nasional, infrastruktur logistik yang lemah menyebabkan distribusi hasil perikanan tidak efisien, memengaruhi daya saing dan harga jual. Produk perikanan Indonesia juga sering gagal menembus pasar ekspor karena tidak memenuhi standar mutu internasional, seperti sertifikasi HACCP, traceability, atau ketentuan sanitary and phytosanitary (SPS).
Di sisi lain, sistem pembiayaan untuk sektor perikanan masih belum berpihak pada nelayan kecil. Lembaga keuangan konvensional masih menganggap sektor ini sebagai sektor berisiko tinggi, dengan tingkat kegagalan tinggi akibat fluktuasi cuaca, pasar, dan hasil tangkapan. Banyak nelayan yang akhirnya bergantung pada rentenir atau tengkulak, yang justru menjerat mereka dalam lingkaran utang. Hal ini semakin diperparah dengan kelemahan kelembagaan nelayan, seperti koperasi yang belum profesional, serta rendahnya literasi keuangan dan kewirausahaan.
Produk-produk perikanan juga sangat tergantung pada penanganan pasca-panen yang efisien. Sebagai contoh, ikan tuna yang diekspor ke Jepang harus memiliki suhu inti maksimal 0°C dan penanganan higienis dari laut hingga pelabuhan. Namun, masih banyak pelabuhan perikanan di Indonesia yang belum memiliki rantai dingin (cold chain) terpadu. Hal ini menyebabkan kerugian pasca-panen bisa mencapai 30% hingga 40%, suatu angka yang sangat besar dalam konteks ketahanan pangan dan efisiensi produksi. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom dan sianida, masih ditemukan di beberapa daerah, merusak ekosistem terumbu karang dan menurunkan produktivitas perikanan jangka panjang.
Globalisasi juga membawa tantangan berupa persaingan produk dari negara lain yang lebih siap dan efisien, seperti Vietnam, Thailand, dan India. Negara-negara ini telah memanfaatkan teknologi modern seperti smart aquaculture, blockchain dalam traceability, hingga pemasaran berbasis digital. Sementara itu, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan teknologi ini secara luas, terutama di kalangan pembudidaya kecil. Padahal, dengan luasnya wilayah perairan dan keberagaman hayati laut, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam inovasi perikanan tropis jika mampu memadukan kearifan lokal dengan teknologi maju.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan inklusif. Pengembangan agribisnis perikanan harus mencakup seluruh rantai nilai, dari produksi, pasca-panen, distribusi, hingga pemasaran. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan melalui pendampingan koperasi, integrasi dengan BUMDes, serta pelatihan manajemen usaha. Pembangunan infrastruktur logistik seperti pelabuhan modern, pabrik es, cold storage, dan transportasi laut terjadwal juga harus menjadi prioritas, terutama di wilayah timur Indonesia yang kaya hasil laut namun miskin fasilitas.
Penting pula untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang ramah bagi sektor perikanan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perikanan dengan bunga rendah harus diperluas dan disosialisasikan dengan baik. Asuransi perikanan yang menjamin risiko gagal panen akibat cuaca atau penyakit juga harus diperluas cakupannya. Selain itu, investor swasta perlu diberi insentif untuk menanamkan modal di sektor ini, dengan menjadikannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau investasi berbasis dampak (impact investment).
Digitalisasi sektor perikanan menjadi salah satu kunci transformasi. Aplikasi e-commerce seperti Aruna, FishLog, atau eFishery telah membuktikan bahwa nelayan dan pembudidaya bisa terhubung langsung dengan pasar nasional dan global melalui teknologi. Pelatihan penggunaan Internet of Things (IoT), sistem informasi geografis (GIS) untuk zonasi tangkap, hingga pelacakan kapal (vessel monitoring system) perlu diperluas untuk menciptakan perikanan yang modern dan berkelanjutan. Generasi muda pun harus dilibatkan secara aktif, baik sebagai inovator, teknokrat, maupun pelaku usaha, agar regenerasi sektor ini tidak terhenti.
Sektor perikanan Indonesia memiliki masa depan yang cerah jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, mulai dari ikan pelagis hingga spesies laut bernilai tinggi seperti tuna, lobster, dan rumput laut. Potensi ini memberikan peluang besar bagi sektor perikanan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan ketersediaan sumber daya alam yang luar biasa dan permintaan pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat, sektor perikanan memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai fondasi dari ekonomi biru yakni sistem ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, jika dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pelestarian, akan membawa manfaat ekonomi yang luas serta menjaga kelangsungan ekosistem laut. Namun demikian, sektor ini tidak lepas dari tantangan serius.
Isu seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), degradasi lingkungan laut, perubahan iklim, hingga keterbatasan teknologi dan akses pasar masih membayangi masa depan perikanan nasional. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sektor perikanan harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, melibatkan kerja sama lintas sektor: pemerintah, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas nelayan. Dibutuhkan pula dukungan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran, termasuk penguatan regulasi, insentif untuk praktik perikanan berkelanjutan, serta investasi di bidang riset dan pengembangan. Masyarakat pesisir, yang merupakan garda terdepan dalam sektor ini, memegang peran vital. Mereka harus diberdayakan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan teknis, informasi pasar, teknologi perikanan modern, dan permodalan yang adil. Pendekatan yang berbasis komunitas dan memperhatikan kearifan lokal akan memperkuat kapasitas mereka untuk menjadi pelaku utama dalam transformasi sektor perikanan yang tangguh dan mandiri.
Dengan strategi pembangunan perikanan yang tepat, perikanan tidak hanya menjadi sektor ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kedaulatan maritim bangsa Indonesia. Ia mencerminkan jati diri kita sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari. Melalui pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sektor ini bisa menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, sekaligus kontributor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berwawasan lingkungan.
You may like
-


Penggunaan Pupuk Kompos Sebagai Strategi Efektif Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Sektor Pertanian
-


Jogja Tak Lagi Romantis untuk Petani
-


Ladang Bisnis dari Si Cantik Bunga Rosela
-


Prosesi Wisuda ke-136, Rektor UIN Jakarta Titip Pesan untuk Wisudawan
-


UIN Jakarta Gelar Wisuda ke-136 dengan Total 1114 Wisudawan
Kolom
Penggunaan Pupuk Kompos Sebagai Strategi Efektif Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Sektor Pertanian
Published
8 bulan agoon
22 Juni 2025By
Cimahi Pos

oleh Nur Indah Rahmadhani
Mahasiswi Jurusan Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Jakarta
Setiap hari, jutaan makanan terbuang sia-sia hanya karena tidak habis di konsumsi. Sayuran yang hanya sedikit layu pun sering kali langsung dibuang begitu saja. Kulit buah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kompos juga turut terbuang. Padahal, fakta menunjukkan bahwa limbah makanan yang termasuk dalam kategori limbah organik adalah salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Konsekuensinya, pemanasan global semakin parah, dampak perubahan iklim semakin terasa. Tentu sangat disayangkan jika potensi makanan yang masih layak dimanfaatkan harus berakhir sebagai sampah.
Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah makanan terbesar, dengan total sekitar 23-48 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Jika seluruh limbah organik ini di kelola dengan bijak melalui pengomposan, tentu akan menjadi sumber daya yang sangat berharga, terutama dalam sektor pertanian. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengolah limbah organik menjadi kompos. Sebagai solusi, di artikel ini akan dijelaskan bagaimana cara mengolah sisa makanan menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk di sektor pertanian.
Sebagai penulis, saya yakin bahwa penggunaan pupuk kompos adalah solusi yang paling masuk akal dan berkelanjutan untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah organik, sekaligus memperbaiki kualitas tanah pertanian untuk jangka panjang. Daripada terus bergantung pada pupuk kimia yang berdampak negatif bagi kesehatan tanah dan ekosistem, kita harus mulai beralih ke solusi yang lebih ramah lingkungan. Kompos bukan hanya sekedar alternatif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim yang kita hadapi.
Pupuk kompos adalah sebuah pupuk organik yang dibuat dari proses dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa tanaman, deadaunan kering, sisa makanan, kotoran hewan, dan juga limbah organik lainnya. Proses ini melibatkan mokroorganisme seperti bakteri, jamur, dan beberapa mikroba lain yang membantu memecah bahan-bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan bermanfaat bagi tanah dan juga tanaman. Fungsi lain dari pupuk kompos yaitu untuk mengurangi erosi dan degradasi tanah.
Selain manfaat ekologis, penggunaan pupuk kompos juga membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Bagi petani, kompos dapat membantu mengurangi biaya pembelian pupuk kimia yang harganya terus melonjak, hasil panen pun meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Secara sosial, pengembangan pengomposan skala rumah tanga hingga komunitas dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti bank sampah organik atau pelatihan keterampilan membuat pupuk kompos. Bahkan, potensi usaha dari produk pupuk kompos pun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan berbagai manfaat tersebut, sudah saatnya penggunaan pupuk kompos dijadikan pilar utama dalam strategi pertanian nasional. Pupuk kompos bukan hanya solusi praktis dan murah, tetapi juga langkah nyata menuju pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keunggulan lain dari pupuk kompos yang sangat penting adalah kemampuannya menyediakan nutrisi makro dan mikro secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah slow-release. Nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur mikra lainnya dilepaskan secara perlahan ke dalam tanah, sehingga tanaman mendapatkan asupan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang musim tanam. Hal ini sangat berbeda dengan pupuk kimi yang cenderung melepaskan nutrisi secara cepat dan berlebihan, yang sering kali menyebabkan pencucian nutrisi ke dalam air tanah dan pencemaran lingkungan. Dengan nutrisi yang dilepaskan secara bertahap tersebut, tanaman dapat menyerap unsur hara secara optimal sesuai kebutuhan, sehingga pertumbuhan menjadi lebih sehat dan hasil panen pun meningkat secara signifikan. Selain itu, pupuk kompos memiliki peran penting dalam memperbaiki keseimbangan biologi tanah. Pupuk kompos mendukung aktivitas miroorganisme tanah yang bermanfaat, seperti bakteri pengikat nitrogen, jamur mikoriza, dan organisme pengurai lainnya. Kehadiran mikroorganisme yang sehat juga dapat membantu mengendalikan pathogen dan hama secara alami, sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
Pupuk kompos terdiri dari berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan bahan baku dan juga metode pengolahannya. Pertama, ada kompos hijau yang terbuat dari bahan-bahan organik segar seperti daun, rumput, atau limbah tanaman muda dengan kandungan nitrogen yang tinggi, sehingga baik untuk empercepat pertumbuhan tanaman. Kedua, terdapat kompos coklat yang berasal dari bahan organik kering seperti jerami, ranting, atau serbuk gergaji, kaya akan karbon dan bermanfaat untuk menyeimbangkan rasio karbon-nitrogen dalam tanah. Ketiga, tersedia juga vermikompos, yaitu kompos hasil proses dekomposisi dengan bantuan cacing tanah (biasanya cacing jenis Lumbricus atau Eisenia foetinida), menghasilkan pupuk dengan kandungan hara tinggi dan tekstur yang remah. Selain itu, ada juga kompos bokashi yakni kompos yang terbuat dengan menggunakan teknik fermentasi anaerob menggunakan bahan tambahan seperti EM4 atau MOL (Mikroorganisme Lokal), prosesnya lebih cepat dan menghasilkan kompos yang sudah di perkaya dengan mikroba bermanfaat, dengan bentuk akhir padat, mirip kompos biasa, teksturnya remah dan agak basah. Selain itu, tersedia juga kompos cair, kompos ini dihasilkan dari fermentasi limbah organik menggunakan mikroba cair seperti MOL atau EM4, brntuk akhirnya yaitu cair seperti larutan nutrisi organi berwarna coklat, mudah diserap tanaman, praktis untuk aplikasi daun. Setiap jenis kompos memiliki kelebihan masing-masing, sehingga pemilihnya perlu disesuaikan kebutuhan spesifik dan situasi di lapangan pada sektor pertanian.
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang ada. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, terbatasnya fasilitas pengomposan di tingkat rumah tangga, dan kurangnya dukungan pemerintah melalui regulasi atau intensif menjadi hambatan besar dalam implementasi penggunaan pupuk kompos secara luas. Banyak yang masih beranggapan pengomposan sebagai proses yang merepotkan, kotor, dan tidak praktis, padahal dengan metode yang tepat, seperti komposter sederhana, proses ini dapat dilakukan dengan mudah bahkan hanya di rumah sendiri.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama mengambil langkah nyata. Mari mulailah dengan memilah sampah organik di rumah dan mengolahnya menjadi kompos sederhana. Ajak sekolah, kampus, dan komunitas lainnya untuk memiliki program edukasi pengomposan. Pemerintah juga perlu hadir lebih aktif dengan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah organik berbasis komunitas, seperti penyediaan fasilitas kompos skala RT/RW, kelurahan, kecamatan, pelatihan gratis, atau intensif bagi rumah tangga yang aktif membuat kompos.
Jika tidak sekarang, maka kapan lagi? Kita harus menyadari bahwa krisis iklim bukanlah ancaman masa depan, melainkan sudah nyata dan jelas di depan mata. Dengan mengubah limbah menjadi berkah melalui pengomposan, kita tidak hanya membantu sektor pertanian tumbuh lebih sehat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestaraian bumi. Kita perlu bergerak bersama-sama, mulai dari langkah kecil di rumah, demi perubahan besar bagi lingkungan. Karena pada akhirnya, bumi bukanlah warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi yang akan dating untuk dijaga dengan maksimal.


oleh Anindita Kyla Putri
Mahasiswi Jurusan Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Jakarta
Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, kini menyimpan kenyataan yang tidak seindah gambaran romantisnya. Di balik geliat pembangunan yang kian pesat, kota ini perlahan kehilangan salah satu identitas utamanya: kehidupan agraris yang damai dan berkelanjutan. Lahan-lahan pertanian yang dulu membentang luas di kaki Merapi dan sepanjang aliran sungai Progo kini berubah wajah. Sawah-sawah menghilang, tergantikan oleh perumahan elit, vila wisata, dan pusat komersial. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2023, lebih dari 1.200 hektare lahan pertanian produktif di DIY telah beralih fungsi hanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi wilayah dengan tingkat konversi tertinggi, menyumbang hampir 70% dari total lahan yang hilang.
Lahan pertanian bukan sekadar ruang untuk menanam padi atau sayur. Ia adalah tumpuan hidup ribuan keluarga petani, penjaga cadangan pangan, serta pelindung lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan pembangunan tak terkendali. Namun ketika lahan berubah menjadi bangunan beton dan aspal, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tapi juga masyarakat secara luas. Ketahanan pangan daerah menjadi rapuh, air tanah semakin sulit diserap, suhu lingkungan meningkat, dan desa-desa kehilangan daya dukung ekologisnya. Dampak lingkungan dari alih fungsi lahan ini semakin terasa di daerah-daerah yang mengalami urbanisasi cepat. Kawasan seperti Godean, Ngaglik, dan Sewon yang dulu sejuk dan hijau kini mulai menghadapi banjir lokal dan suhu udara yang makin panas.
Kehidupan petani menjadi kelompok yang paling terdampak dari alih fungsi lahan. Banyak di antara mereka kehilangan sebagian atau seluruh lahan garapan karena terdesak kebutuhan ekonomi dan minimnya dukungan kebijakan. Ketika hasil panen tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjual tanah menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil. Ironisnya, lahan yang dijual tersebut kerap kali berubah menjadi perumahan, hotel, atau vila yang dibangun tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem desa. Para petani yang sebelumnya memiliki otonomi atas tanah kini berubah menjadi buruh kasar atau pekerja informal dengan penghasilan tidak menentu. Kehilangan lahan berarti kehilangan sumber produksi, penghidupan, serta posisi sosial yang selama ini melekat erat dengan identitas mereka sebagai penjaga bumi dan penyedia pangan. Transformasi ruang ini bukan hanya mengubah fungsi lahan, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan budaya yang telah lama tumbuh di masyarakat agraris.
Konversi lahan juga menciptakan krisis regenerasi petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pada tahun 2022 hanya 9,3% pemuda usia 18–35 tahun yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar lebih memilih menjadi ojek daring, pekerja kafe, atau merantau ke kota besar karena menganggap bertani tidak menjanjikan secara ekonomi. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan pertanian jangka panjang. Ketika tidak ada generasi penerus yang mau menggarap lahan, maka sawah yang tersisa pun terancam tidak terurus atau dijual ke pihak luar.
Di sisi kebijakan, pembangunan seringkali tidak berpihak pada petani. Pemerintah daerah cenderung mendorong ekspansi sektor pariwisata dan properti sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun langkah ini kerap mengabaikan perlindungan atas lahan pertanian. Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kerap kali direvisi demi mengakomodasi kepentingan investor, bukan menjaga ruang hidup rakyat kecil. Dalam banyak kasus, petani tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya diberi informasi sepihak ketika tanah mereka akan dialihfungsikan. Bahkan di beberapa tempat seperti Imogiri dan Kalasan, konflik agraria muncul karena petani menolak menyerahkan tanah mereka untuk proyek wisata atau jalan tol.
Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari konversi lahan memang tampak menjanjikan dalam jangka pendek. Sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan meningkat tajam. Namun dalam jangka panjang, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar. Ketika produksi pangan lokal menurun, DIY akan semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan ini menjadikan Yogyakarta rentan terhadap krisis distribusi pangan, terutama saat terjadi gangguan logistik atau fluktuasi harga nasional. Kota yang kehilangan kemampuan untuk memberi makan penduduknya sendiri adalah kota yang kehilangan kemandirian. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, maka kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon kosong dalam dokumen perencanaan daerah.
Pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas dalam menjaga lahan pertanian yang tersisa. Penetapan zona pertanian abadi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh diubah demi kepentingan investasi sesaat. Perlu ada pengawasan ketat terhadap pelanggaran konversi dan pemberian sanksi terhadap pengembang yang melanggar aturan zonasi. Pemerintah juga harus memperkuat lembaga perlindungan petani agar mereka memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola. Selain itu, penting juga mendorong sinergi antara kampus, petani, dan pemerintah daerah untuk riset pertanian berkelanjutan. Kemitraan ini bisa mendorong inovasi bibit lokal, diversifikasi komoditas, hingga kebijakan distribusi hasil tani yang lebih adil dan transparan.
Insentif bagi petani harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Bantuan alat dan teknologi pertanian, subsidi benih dan pupuk, serta pelatihan pertanian organik dan berkelanjutan harus digencarkan. Koperasi tani perlu didukung untuk memperkuat posisi tawar petani di pasar. Akses pembiayaan pertanian melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan program pendampingan juga harus dipermudah, agar petani tidak lagi terjebak utang dengan bunga tinggi dari tengkulak. Edukasi finansial dan literasi pasar juga penting diberikan kepada komunitas tani agar mereka bisa bertahan di tengah gempuran sistem distribusi modern yang tidak selalu adil.
Langkah inovatif seperti pengembangan pertanian urban, kebun komunitas, dan hidroponik di lingkungan kota juga dapat menjadi solusi untuk menjaga produksi pangan lokal di tengah keterbatasan lahan. Pemanfaatan lahan tidur di perkotaan untuk pertanian skala kecil bisa menjadi alternatif yang mempertemukan kebutuhan pangan dengan gaya hidup masyarakat urban yang lebih sadar lingkungan. Yogyakarta, dengan kekayaan intelektual dari kampus-kampus ternama dan komunitas kreatif, memiliki modal kuat untuk menjadi pelopor pertanian berbasis ekologi dan teknologi terapan. Kolaborasi lintas sektor ini akan sangat menentukan apakah pertanian di Jogja akan bertahan, atau justru hilang perlahan dalam diam.
Romantisme Jogja selama ini tumbuh dari kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan kehidupan desa yang bersahaja. Namun jika lahan pertanian terus dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, maka Jogja akan kehilangan jiwanya. Kota ini akan berubah menjadi ruang konsumsi semata, indah bagi pelancong, tapi menyisakan luka bagi petani dan warga lokal. Yang dulu membangun kehidupan dari tanah kini tersingkir dari tanahnya sendiri. Jika tidak ada keberanian politik untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlangsungan pertanian, maka masa depan DIY sebagai daerah yang berdaulat pangan dan berakar pada kearifan lokal hanya akan menjadi mitos belaka.
Petani tidak butuh pujian dalam syair atau penghargaan seremonial. Mereka butuh perlindungan yang nyata, dukungan kebijakan yang berpihak, dan pengakuan atas peran vital mereka dalam menjaga pangan, budaya, dan lingkungan. Jogja yang istimewa seharusnya menjadi tempat di mana petani bisa bertahan hidup dengan bermartabat, lahan dijaga sebagai warisan bersama, dan pembangunan dilakukan dengan adil serta berkelanjutan. Hanya dengan itu, Jogja bisa tetap romantis — bukan dalam kenangan, tetapi dalam kehidupan nyata mereka yang selama ini menumbuhkan peradaban dari tanah yang mulai ditinggalkan.


oleh Jumrotun Naimah
Mahasiswi Jurusan Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Jakarta
Di zaman sekarang ini, tren gaya hidup sehat menjadi bagian terpenting dalam menjaga daya tahan tubuh supaya lebih terjaga dari berbagai macam penyakit. Masyarakat semakin sadar terhadap produk alami dan ramah lingkungan. Bunga Rosela hadir sebagai tanaman yang bisa diolah untuk produk herbal, tanaman ini tidak hanya cantik secara visual tetapi juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Bunga rosela menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan karena dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi.
Rosela (Hibicus sabdariffa Liin) merupakan tanaman dari famili Malvaceae yang berasal dari benua Afrika, terutama dari wilayah Sudan. Bagian dari tanaman rosela yang sering digunakan yaitu bunganya. Rosela dikenal dengan kelopak bunga yang berwarna merah cerah hingga keunguan. Budidaya Rosela yang terbilang cukup sederhana, dengan masa panen yang relatif singkat sekitar 3-4 bulan setelah masa tanam. Rosela bisa beradaptasi untuk tumbuh di berbagai iklim, baik di ilkim tropis maupun subtropis dengan tanah yang subur, sehingga Indonesia merupakan wilayah yang cocok untuk mendukung budidaya bunga rosela. Di Indonesia rosela sangat mudah dijumpai karena tergolong tanaman rumahan dan tidak memerlukan perawatan khusus, oleh sebab itu masyarakat bisa dengan mudah memanfaatkan dan membudidayakannya.

Rosela (Hibicus sabdariffa Liin) mengandung vitamin C (asam askorbat) dalam jumlah kadar yang cukup tinggi, oleh karena itu kelopak bunga rosela menghasilkan rasa masam. Bahkan kandungan vitamin C dalam rosela (260-280 mg per gram) lebih tinggi dibandingkan dengan buah jeruk (50 mg per 100 gram). Selain itu, bunga rosella memiliki beberapa kandungan zat seperti gossypetin, glukosida, hibiscin, flavonoid, theflavin, katekin dan antosianin. Antosianin pada bunga rosela mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit kardiovaskuler, termasuk penyakit hipertensi. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa rosela mampu membantu menurunkan kadar kolesterol, menurunkan demam, mengatasi diabetes dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak heran jika rosela sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dan kini mulai menarik perhatian industri farmasi serta produk kesehatan yang alami.
Dengan beragam manfaat kesehatan yang dimilikinya, rosela memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan herbal yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu produk yang populer yaitu teh herbal rosela, minuman khas yang diseduh dari kelopak kering dan dikenal dengan rasa asam yang menyegarkan dan kaya manfaat kesehatan. Dibalik manfaat kesehatan tersebut, teh herbal rosela memiliki sejarah panjang yang menarik. Di tanah asalnya, Afrika, rosela dikenal dengan nama “karkadeh” atau “karkady” yang telah lama digunakan sebagai minuman tradisional. Melalui jalur perdagangan dan pengaruh kolonialisme, rosela menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, Asia, Amerika, hingga Australia. Di Mesir, karkadeh diperkenalkan oleh para pedagang Arab dan berkembang menjadi bagian penting dari budaya kuliner lokal, khususnya dalam perayaan pernikahan dan selama bulan Ramadan. Perjalanan rosela yang melintasi benua ini menjadikannya tidak hanya bermanfaat secara kesehatan, tetapi juga kaya akan nilai sejarah dan budaya.

Selain itu, rosela juga dapat diolah menjadi sirup. Sirup rosela dibuat dari rebusan kelopak bunga rosela yang dicampur dengan gula, menghasilkan warna merah cerah alami dengan aroma dan rasa yang khas asam-manis menyegarkan. Sirup rosela memiliki potensi besar sebagai minuman sehat yang digemari masyarakat modern yang mulai beralih ke produk alami dan fungsional. Selain dikemas sebagai minuman siap saji, sirup ini juga bisa dijadikan campuran dalam es krim, puding, yoghurt, atau topping dessert, sehingga membuka peluang usaha baik untuk skala rumahan maupun industri.
Warna merah alami yang dihasilkan dari bunga rosela dapat digunakan sebagai pewarna makanan yang aman. Kelopak rosela memiliki kandungan pigmen antosianin, sehingga dapat menghasilkan warna merah yang stabil dan cocok untuk dijadikan pengganti pewarna sintetis. Kebutuhan pasar terhadap pewarna alami yang aman dan sehat terus meningkat, menjadikan rosela sebagai salah satu sumber bahan baku yang menjanjikan.

Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan, ekstrak rosela yang kaya akan antioksidan juga dimanfaatkan dalam dunia kecantikan. Kandungan alaminya dipercaya mampu membantu mencegah penuaan dini dan melindungi kulit dari dampak buruk sinar UV, menjadikannya bahan populer dalam berbagai produk perawatan kulit.
Lebih dari sekadar tanaman herbal, rosela juga menyimpan potensi dalam sektor industri. Batangnya mengandung serat bast yang kuat dan berkualitas tinggi, sehingga cocok dijadikan alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan serat sintetis. Serat ini telah digunakan dalam pembuatan tekstil, komponen otomotif, bahan isolasi, hingga produk komposit yang mendukung prinsip keberlanjutan.
Namun, dibalik manfaatnya yang luar biasa dan memiliki potensi bisnis yang menjanjikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan bisnis rosela menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat rosela. Banyak yang masih menganggap tanaman ini sekadar tanaman hias atau bahkan gulma, sehingga potensi ekonominya belum tergali secara maksimal. Selain itu, terbatasnya akses pasar dan minimnya promosi membuat produk olahan rosela sulit dikenal secara luas. Produktivitas rosela juga menjadi tantangan tersendiri karena mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti serangan hama, perubahan iklim yang tidak menentu, dan fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat rosela, agar tidak dianggap lagi sebagai tanaman biasa. Akses pasar juga perlu diperluas dengan promosi yang menarik melalui platform digital. Selain itu, penerapan teknik budidaya yang tepat serta dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan pemasaran dapat membantu menjaga hasil panen tetap optimal dan harga rosela tetap stabil di pasaran.
Bunga rosela layak diberi perhatian lebih sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai kesehatan dan ekonomi tinggi. Di tengah maraknya minum pabrikan yang tinggi gula dan pewarna sintetis, rosela hadir sebagai solusi produk minuman yang lebih sehat. Berkat kandungan antioksidannya rosela bermanfaat di bidang kecantikan, serta memiliki potensi industri melalui serat batangnya yang ramah lingkungan. Dengan berbagai manfaat dan potensi yang dimilikinya, rosela semakin terbukti sebagai tanaman multifungsi yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat di era modern, sekaligus mendorong kesejahteraan petani dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Bayangkan jika tiap desa di Indonesia mampu menghasilkan produk olahan rosela, dengan kemasan menarik dan pamasaran digital yang kuat. Tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi bisa membangun citra lokal yang sehat dan ramah lingkungan. Contohnya di Malang, para ibu rumah tangga di Desa Sumberdem mengembangkan berbagai olahan rosela seperti teh, dodol, dan minuman herbal melaui Klaster Rosella yang didukung oleh BRI dalam program “KlasterkuHidupku”. Sementara itu, di Cirebon, seorang pelaku UMKM berhasil menjual sirup rosela dengan omzet hingga 16 juta per bulan. Peran anak muda juga penting dalam hal ini karena mereka mempunyai kreativitas yang tinggi untuk mengubah rosela menjadi produk inovatif yang diminati pasar.
Rosela merupakan contoh nyata bahwa alam menyediakan tanaman yang indah, menyehatkan, dan menguntungkan. Dengan kelopak merahnya yang memikat serta kandungan gizi yang luar biasa, rosela pantas dijadikan ikon bisnis herbal masa depan. Jika kita mampu menggabungkan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan, maka si cantik bunga rosela ini bisa menjadi ladang bisnis bagi siapa saja yang mau merawat dan mengembangkannya.
Mari kita mulai memandang bunga rosela bukan hanya sebagai tanaman biasa, melainkan sebagai gerbang menuju masa depan ekonomi herbal yang sehat dan berkelanjutan. Saatnya kita bergerak bersama petani, generasi muda, dan pemerintah untuk menjadikan rosela sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan inovasi.
Kolom
Perkembangan Peluang Agribisnis di Era Industri Digital 4.0
Published
8 bulan agoon
20 Juni 2025By
Cimahi Pos

oleh Farizha Rahma Ayu Anggita
Mahasiswi Jurusan Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Jakarta
Pada era industri digitalisasi 4.0 saat ini manusia telah merasakan sejumlah perubahan khususnya dalam inovasi teknologi yang mendorong segala aktivitas yang terjadi untuk mengikuti arus perubahan ini. Salah satu hal yang mendorong perubahan yang terjadi pada dunia saat ini adalah pandemi Covid-19. Saat itu dunia diharuskan untuk menghentikan segala kegiatan yang ada dengan diam dirumah (lockdown) dan segala macam kegiatan dilakukan berdasarkan daring (online) hal ini, yang memicu perkembangan teknologi secara cepat.
Perubahan teknologi ini dirasakan pada berbagai sektor, khususnya dalam sektor agribisnis. Era industri 4.0 yang terjadi ini ternyata membawa dorongan perubahan yang cukup berpengaruh didalam sektor agribisnis, seperti adanya sistem toko yang dilakukan secara daring (online shop), adanya integrasi teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), dan kemunculan kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, para petani dan juga para pelaku agribisnis harus melakukan sejumlah inovasi dalam memanfaatkan perubahaan teknologi yang ada pada saat ini.
Sektor agribisnis merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Perannya yang strategis tidak hanya dalam penyediaan bahan pangan, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadikan sektor ini sangat vital. Menurut data BPS (2022), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang sekitar 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Akan tetapi, seiring dengan masuknya era industri digital 4.0, sektor agribisnis dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi agar tetap kompetitif dan relevan.

Dalam perkembangan teknologi digital ini membuka beragam macam peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku agribisnis yaitu sebagai alat dan sistem yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis pertanian, mulai dari budidaya, panen, pasca-panen, distribusi, hingga pemasaran. Inovasi yang ada pada industri digital saat ini mencangkup strategi penggunaan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan.
Namun, ternyata dalam praktiknya masih banyak para petani dan pelaku agribisnis yang tidak mengetahui apalagi memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, di
Indonesia sendiri sejumlah daerah ataupun pada pelosok daerah yang terpencil, teknologi yang telah berkembang masih tidak dapat dijangkau oleh para petani dan pelaku agribsinis. Survei Kementerian Pertanian (2021) menunjukkan bahwa hanya 29% petani di Indonesia yang sudah memiliki akses terhadap teknologi berbasis internet, dan dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang benar-benar menggunakannya dalam proses produksi atau pemasaran. Ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup; butuh pendekatan yang bersifat manusiawi dan kolaboratif agar transformasi ini benar-benar inklusif.
Padahal faktanya penggunaan teknologi ini dapat membantu proses pertanian dan sektor agribsinis agar dapat lebih berkembang lagi. Menurut Nurdiyah dalam jurnal reposity di Universitas Terbuka, adopsi teknologi digital memungkinkan pelaku agribisnis untuk memantau dan mengelola tanaman, ternak, serta sumber daya alam dengan lebih baik. Hal ini akan membantu dalam mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, serta mengurangi pemborosan dan dampak pencemaran lingkungan secara negatif.
Peluang dalam penerapan teknologi digital pada sektor agribisnis masih banyak yang dapat dimanfaatkan seperti penerapan teknologi pada pertanian dengan menggunakan sensor otomatis yang dapat digunakan untuk mengecek kondisi tanah, seperti tingkat keasaman tanah, suhu dan kelembapan tanah secara optimal, atau penggunaan teknologi digital yang dapat memungkinkan pelacakan dan pemantauan langsung dari produksi hingga konsumsi, sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan keamanan pangan.
Teknologi industri digitalisasi saat ini bahkan mampu memberikan peringatan dini terhadap perubahan cuaca ekstrem atau serangan hama penyakit, yang mana teknologi ini dapat memberikan informasi yang sangat penting bagi petani dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat artinya perkembangan teknologi digital dalam sektor agribisnis ini sebenarnya menyimpan sejumlah potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam usaha tani.
Akan tetapi, fakta dan teori pun cukup berbeda, kenyataan di lapangan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak semua pelaku agribisnis memiliki pemahaman atau akses terhadap teknologi ini, yang kemudian menjadi hambatan tersendiri dalam upaya perubahan digital pada sektor agribisnis di Indonesia. Yakni, adanya sejumlah tantangan besar yang terjadi pada sektor agribisnis pada penerapan teknologi digitalisasi ini.
Salah satu masalah yang paling krusial adalah rendahnya literasi digital di kalangan petani, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dengan akses pendidikan dan teknologi yang sangat terbatas. Banyak dari mereka tidak memiliki smartphone, tidak tahu cara mengoperasikan aplikasi berbasis data, dan bahkan belum pernah bersentuhan dengan teknologi. Masih banyak petani yang merasa ragu dan takut mencoba teknologi baru karena merasa tidak mampu mengoperasikannya. Mereka juga merasa belum yakin terhadap manfaat jangka panjang yang bisa mereka dapatkan dari penggunaan teknologi tersebut.
Ditambah dukungan pemerintah yang tidak merata pada sejumlah daerah dalam mendukung perkembangan agribisnis di era digitalisasi ini sangat berpengaruh. Seharusnya pemerintah daerah setempat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung perkembangan teknologi dalam sektor agribisnis. Padahal jika pemerintah melakukan pendekatan yang tepat dalam mengedukasi para petani dan pelaku agrbisnis maka, sejumlah peluang terbuka lebar untuk sektor agribisnis dalam penggunaan teknologi.
Salah satu solusi konkret yang dapat diambil adalah kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur digital di daerah tertinggal dengan cara memperluas jaringan internet desa dan memberikan insentif berupa subsidi alat pertanian digital bagi petani. Perguruan tinggi, melalui program pengabdian masyarakat, harus aktif memberikan pelatihan teknologi, mulai dari penggunaan aplikasi hasil panen, pengelolaan data keuangan tani, hingga cara menjual produk secara online. Sektor swasta dapat menciptakan perangkat lunak dan aplikasi ramah pengguna yang mudah diakses oleh petani, termasuk dalam bahasa lokal.
Menurut penulis keterlibatan dari segala pihak yang ada dalam mendukung perkembangan sektor agribinis ini dapat meyakinkan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani kesenjangan ini. Generasi muda merupakan kelompok yang paham teknologi sekaligus memahami kondisi petani atau pelaku agribisnis dengan terjun langsung ke lapangan. Maka dari itu, peran mahasiswa tidak hanya sebatas belajar di kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mengedukasi dan menginspirasi petani dan pelaku agribsnis agar tidak takut menghadapi kemajuan zaman.
Pendampingan yang dilakukan secara langsung dan pendekatan yang personal akan jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan petani atau pelaku agribisnis terhadap teknologi. Generasi muda harus mampu menjadi penghubung antara dunia teknologi yang cepat berkembang dan dunia pertanian yang selama ini berjalan perlahan. Dengan begitu, proses perubahan industri digital akan menjadi lebih manusiawi dan berakar dari bawah, bukan hanya didorong dari atas secara sepihak.
Dengan demikian, perkembangan peluang agribisnis di era Industri Digital 4.0 ternyata sangatlah besar dan menjanjikan. Namun, di balik itu semua potensi tersebut, ada sejumlah tantangan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu rendahnya literasi digital dan ketimpangan akses teknologi di kalangan petani dan para pelaku agribisnis. Perubahan digital tidak bisa berjalan efektif jika hanya sebagian kecil pelaku agribisnis yang mampu mengakses dan memanfaatkannya.
Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan petani serta para pelaku agribisnis itu sendiri agar perubahan ini bisa dirasakan oleh semua kalangan. Dengan harapan bahwa masa depan pertanian Indonesia adalah pertanian yang modern tapi tetap inklusif, berbasis teknologi tapi tetap memihak petani kecil, dan berorientasi pasar tapi tetap menjunjung keberlanjutan. Teknologi hanyalah alat, tapi manusialah yang akan menentukan ke mana arah agribisnis Indonesia ke depan.


Penting! Ini Urutan Wali Nikah bagi Pengantin Perempuan

Hukum Memejamkan Mata ketika Shalat

Jelang Pemulangan Gelombang II, Jemaah Haji Diminta Patuhi Aturan Barang Bawaan

Menag Promosikan Pancasila dan Diversity di Forum Internasional Singapura

Rucky Markiano: Lagu “Biru,.. Bukan Maksudku” Bikin Air Netes Segaris-Segaris, Idung Mampet!

Hukum Makan dan Minum Sambil Berdiri
Trending
-

 News8 bulan ago
News8 bulan agoMenag Promosikan Pancasila dan Diversity di Forum Internasional Singapura
-
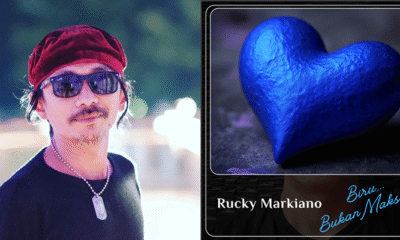
 Showbiz8 bulan ago
Showbiz8 bulan agoRucky Markiano: Lagu “Biru,.. Bukan Maksudku” Bikin Air Netes Segaris-Segaris, Idung Mampet!
-

 Hikmah9 bulan ago
Hikmah9 bulan agoHukum Makan dan Minum Sambil Berdiri
-

 News8 bulan ago
News8 bulan agoJelang Pemulangan Gelombang II, Jemaah Haji Diminta Patuhi Aturan Barang Bawaan
-

 Cimahi248 bulan ago
Cimahi248 bulan agoPKBM PP Riyadhul Mahirin Kota Cimahi Gelar Pelepasan Kelulusan Siswa
-

 Piknik9 bulan ago
Piknik9 bulan agoComic Frontier XX, Pasar Kreatif Terbesar di Indonesia Kembali Digelar 24–25 Mei 2025 di ICE BSD
-

 Campernik10 bulan ago
Campernik10 bulan agoPemkot Cimahi Targetkan Koperasi Merah Putih Terbentuk di 15 Kelurahan
-

 Kolom8 bulan ago
Kolom8 bulan agoPenggunaan Pupuk Kompos Sebagai Strategi Efektif Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Sektor Pertanian
-

 Cimahi248 bulan ago
Cimahi248 bulan agoKelurahan Cimahi Gelar Lomba Karedok, Usung Tema Mesat Mantap Makin Happy

